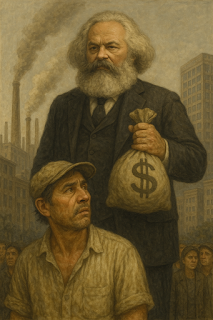By Yasrin A. Abas, Safrin Lamusrin
Gambar Ilustrasi
Setiap tahun, ribuan mahasiswa dari
berbagai pelosok daerah kembali ke kampung halamannya setelah menyelesaikan
pendidikan tinggi dengan segudang pengalaman, wawasan baru, dan semangat
perubahan. Namun yang sering terjadi bukanlah sambutan hangat atau penyaluran
potensi, melainkan keterasingan, ketidakpercayaan, bahkan pengabaian. Mahasiswa
yang dulunya aktif berorganisasi, kritis terhadap isu sosial, dan penuh
inovasi, justru merasa "kembali tanpa ruang" di tengah masyarakatnya
sendiri.
Fenomena ini menyisakan pertanyaan besar: mengapa potensi dan energi besar yang dimiliki para mahasiswa tidak mampu terserap secara optimal di daerah asal mereka? Mengapa para agen perubahan ini justru terpinggirkan, dianggap terlalu idealis, atau bahkan menjadi ancaman bagi kenyamanan status quo? Apakah ini sepenuhnya kesalahan mahasiswa, atau justru ada kegagalan sistemik dalam tata kelola daerah dan budaya lokal?
Kondisi mahasiswa yang pulang ke kampung halaman namun tidak diberi ruang aktualisasi
bukanlah cerita baru. Banyak dari mereka yang telah menempuh pendidikan tinggi dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata di daerahnya, justru merasa tidak diakui atau bahkan diabaikan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksinambungan antara dunia akademik dan realitas sosial-politik di daerah. Beberapa Fakta menunjukan diantaranya :
Pertama, Salah satu persoalan utama adalah ketiadaan ekosistem yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam pembangunan lokal. Banyak daerah belum memiliki wadah yang inklusif bagi generasi muda, seperti forum pemuda yang substantif, inkubator kewirausahaan lokal, atau kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan alumni kampus. Hal ini membuat semangat inovatif mahasiswa seperti terhenti di pintu gerbang kampung halaman mereka sendiri.
Kedua, Di beberapa daerah, kultur sosial yang sangat hierarkis membuat suara mahasiswa sering dianggap belum pantas didengar. Pengalaman organisasi dan kepemimpinan mereka kerap tidak dianggap karena status usia, ketidakterlibatan dalam “struktur kekuasaan lokal,” atau bahkan dianggap sebagai “pembangkang” karena cara berpikir mereka yang kritis. Ini menciptakan jarak psikologis antara mahasiswa dan tokoh-tokoh lokal, serta menyuburkan sikap skeptis terhadap kontribusi kaum muda.
Ketiga, Dalam banyak kasus, tidak ada jembatan yang menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan praktis daerah. Padahal, mahasiswa adalah bagian dari “produk” pendidikan tinggi yang idealnya mampu menjawab tantangan lokal. Sayangnya, pemerintah daerah jarang menjadikan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pembangunan. Akibatnya, mahasiswa yang pulang pun tidak tahu harus ke mana membawa ide dan keahliannya.
Yang keempat Di sisi lain, sebagian mahasiswa juga datang dengan semangat besar namun minim strategi komunikasi sosial. Gagasan mereka bagus, tetapi penyampaiannya tidak memperhitungkan konteks budaya, struktur sosial, dan norma masyarakat setempat. Ini membuat niat baik mereka disalahpahami, atau bahkan dianggap menggurui.
Fenomena mahasiswa yang “kembali tanpa ruang” mencerminkan kegagalan sistemik dalam
menyinergikan potensi kaum terdidik dengan pembangunan daerah. Di satu sisi, mahasiswa datang dengan bekal intelektual, pengalaman organisasi, dan semangat perubahan. Namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa daerah tidak memiliki sistem yang siap menampung, apalagi memberdayakan energi tersebut. Budaya sosial yang hierarkis, lemahnya kolaborasi antar lembaga,
hingga minimnya ruang partisipasi publik menjadikan kontribusi mahasiswa terhenti sebelum sempat dimulai. Ini bukan semata kegagalan individu, tetapi juga kegagalan struktural yang perlu disadari dan dibenahi secara kolektif.
Oleh karena itu penulis merekomendasikan beberapa saran diantaranya : (1). Pemerintah DaerahPerlu Membuka Ruang Partisipasi yang Nyata bagi Kaum Muda Pemerintah daerah sebaiknya membentuk forum kolaboratif yang melibatkan mahasiswa, alumni kampus, dan tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal. Ruang ini harus bersifat terbuka, setara, dan menjamin bahwa ide serta kritik mahasiswa tidak hanya didengar, tapi juga diakomodasi dalam kebijakan. (2). Kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah penting untuk menjembatani potensi mahasiswa dengan kebutuhan lokal. Program seperti Kuliah Kerja Nyata Tematik, magang di instansi daerah, atau riset terapan berbasis kebutuhan lokal bisa menjadi jembatan efektif. (3) Mahasiswa juga perlu dibekali kemampuan literasi sosial dan komunikasi lintas generasi. Kemampuan membaca konteks budaya, bersikap rendah hati, serta membangun relasi sosial yang kuat dengan masyarakat setempat adalah kunci agar gagasan mereka diterima dan dapat diwujudkan.